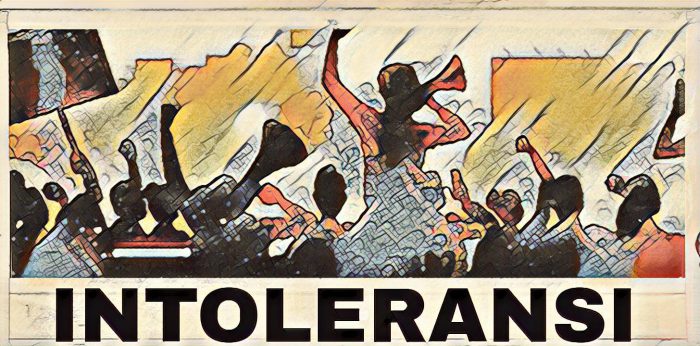
Intoleran, Etnosentris Wilayah Abu-abu. Kolase Sosiologi
Oleh: Slamet Hendro Kusumo
Akhir-akhir ini kita terus diguncang oleh isu-isu tentang intoleransi. Lawan intoleransi adalah toleransi. Toleransi adalah sebuah proses akumulasi keyakinan, dari ruang privat menjadi terbuka. Mau memahami dan menyadari akan keberbedaan dan keberadaan orang lain. Yang berbeda agama, RAS dan suku. Oleh karenanya relasi sosial ini tidak saja mengokohkan antara hubungan pribadi yang berbeda. Akan tetapi mengikat erat hadirnya negara bangsa yang memiliki sistem kesatuan plural.
Sedangkan intoleransi adalah memiliki sifat, watak “lebih tertutup” dan cenderung menyerang orang lain. Sebab orang lain dianggap tidak benar dan mengganggu atau menghalangi keberadaan kaum intoleran. Sikap intoleran tersebut berpotensi, melawan jika tindakan-tindakan intoleran itu selalu membuat ulah dan terus merong-rongnya kepada kaum toleransi. Dua arus besar ini selalu berhadapan hampir setiap saat, tidak pernah lelah. Bahkan menjadi-jadi saat para “pemilik kepentingan” itu ikut di dalamnya. Terjadilah polarisasi dan politisasi.
Bertens: etika dalam pengertian moral menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika adalah kumpulan asas atau nilai moral berisikan tentang apa yang baik atau yang buruk.
Semua pergerakan intoleran, difokuskan dalam pembahasan ini. Telah distigmakan sebagai penggangu lingkungan dan negara bangsa. Seperti diketahui, hari ini sikap intoleran sudah tidak lagi murni. Intoleran masa lalu, ada ideal dan tujuan akan kekuasaan. Utamanya yang berbasis masa dengan desain organisasi lokal atau kelompok lokal. Tujuan kelompok dan organisasi lokal tersebut adalah bersifat “murni ideologis”. Kelompok ini ada dua desain. Desain pertama adalah terkait dengan kelompok intoleran berbasis etnosentris. Sedangkan desain kedua intoleransi tersebut berbasis agama. Keduanya memiliki sensitifitas sangat tinggi. Bahkan saling ganggu karena bertahan pada sugestifitas dan ideologis masing-masing. Intoleransi berbasis etnosentris, sebagai “pemilik wilayah adat”. Ada kecenderungan mempertahankan “kerukunan, dalam basis nilai-nilai yang sudah dibentuk leluhur”.
Sudah berabad-abad dibangun dan teruji melahirkan generasi-generasi yang sesuai dicitakan. Kelompok toleransi ini disebut toleransi yang eksklusif. Sedangkan toleransi yang terbuka atau inklusif dapat menerima berbagai masukan atau kehadiran dari budaya lain. Sepanjang tidak mengganggu nilai-nilai yang dibangunnya. Sedangkan intoleransi menjadi arah kebalikan bersifat tidak menyetujui dan merasa jenuh dengan kondisi-kondisi masa lalu, apapun nilainya. Menginginkan adanya perubahan serta berkehendak untuk menguasainya.
Oleh sebab itu gerakan intoleransi “lebih agresif” sebagi pengganggu yang potensial. Akan menjadi lebih brutal lagi ketika sudah dimasuki oleh “anasir-anasir asing”. Yang dimaksud anasir asing, bisa kaum urban atau “kerangka-kerangka konspirasi”. Yang berkecenderungan telah membuat grand design, dengan ruang lingkup lebih besar. Antara lain ingin mengubah citra negara, ideologi, ekonomi dan budaya.
Gerakan-gerakan intoleransi inilah, telah memberikan efek menakutkan, bagi masyarakat umum, yang telah dibentuk oleh rasa aman masa lalu. Gerakan tersebut tidak saja mengubah cara pandang individu, akan tetapi juga memiliki kemampuan sangat baik, dalam mengelola isu-isu, berbasis kebohongan-kebohongan, secara terus menerus. Sehingga kebohongan itu seolah-olah menjadi kebenaran baru yang masuk akal.
Habermas: untuk mencapai konsensus nasional tentang klaim moral, yakni keadilan sosial yang manifes.
Sebagai negara demokrasi yang menjadi pilar republik, memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam menyampaikan pendapat. Kemerdekaan berbicara, berkelompok dan berorganisasi. “Ruang fana” ini sering diasumsikan sebagai “ruang tak bertuan”. Siapapun boleh berpendapat dari yang santun hingga yang banal, liar dan jauh dari etika. Jika negara bangsa sedikit saja membuat penertiban-penertiban, maka kaum intoleran, mengkritik tindakan negara tersebut sebagai ditaktor, tiran, tidak demokratis, kriminalisasi serta segala macam tuduhan-tuduhan lain, sebagai “gugatan atas nama kebebasan berpendapat”.
Inilah isu-isu sentral sebagai jualan yang tak pernah habis digali. Kaum intoleran itu memiliki “kecerdasan tingkat dewa”, bisa menempel di segala kepentingan. Kecanggihan kaum intoleran adalah “mengelola isu-isu sensitif agama”. Sebab negara-negara yang berbasis agama mayoritas bisa dijadikan sebagai alat kritik untuk menuju “tebar pesona” secara sistemik dan masif. Dicontohkan ketika ada demo-demo ketidakpuasan, dapat dipantau, beberapa keluarga dilibatkan, bahkan anak-anak kecil juga balita. Ada “faktor kesengajaan” jika terjadi konflik, dan memakan korban, akan dijadikan martil hebat untuk argumen-argumentasi tentang runtuhnya dalil-dalil kemanusiaan, yang dilanggar oleh pemerintah.
Silang sengkarut ini menjadi semakin rumit, ketika sudah dikonotasikan sebagai perang entitas atau etnosentris. Perang kaum Kadrun dan Cebong, ledekan etnosentris, dengan simbol-simbol hewan sebagai ungkapan-ungkapan emosional kelompok demonstran tersebut.
Disorientasi Etnosentris
Paradigma etnosentris, adalah cara berpikir dari kebiasaan suatu etnis, menganggap dirinya lebih unggul. Baik secara RAS maupun keunggulan genetic. Atau dengan kata lain, etnosentris memiliki potensi dalam menilai kelompok yang lain, tidak lebih baik dari kelompoknya. Memang ada saja pendapat yang mennggolongkan, bahwa etnosentris beda tipis dengan primordialisme. Kesamaannya adalah ada yang bersifat terbuka, artinya bahwa etnosentris yang masih mau menerima kultur lain. Dapat hidup berdampingan asalkan tidak diganggu. Demikian juga primordialisme. Akan tetapi dapat saja menjadi agresif, bagi yang sulit menerima perubahan. Sensitifitas etnosentri, bukan saja persoalan-persoalan gangguan namun juga menjadi gaya hidup.
Aristoteles: berpolitik adalah cermin beretika. Sebab tanpa dimensi politik manusia belum bisa disebut manusia.
Oleh sebab itu sangat berpotensi sekali jika sensitifitas ini “digoreng” dengan pihak-pihak yang berkepentingan kepada kuasa politik, ekonomi, sosial. Maka akan tumbuh menjadi radikalisme dan intoleran. Intinya intoleran bisa terjadi pada setiap kultur atau kelompok yang sudah pada posisi “zona nyaman” seperti dikatakan oleh Adellman dan Levine, bahwa etnosentrisme memiliki derajat yang melekat pada seseorang. Oleh karenya berpotensi menjadi kesuksesan sekaligus kegagalan komunikasi lintas budaya. khususnya ketika individu memasuki lingkungan budaya baru.
Dalam kasus-kasus serius dan perlu perhatian serius, bagi kaum moralis negara bangsa, banyak terjadi konflik berkepanjangan. Menjadi target “gorengan, untuk mencapai tujuan politik kekuasaan”. Biasanya kelompok-kelompok intoleran yang sudah terdesain dengan rapi, berpotensi juga untuk mempunyai tujuan untuk berkuasa. Hal itu, polanya bisa menjadi “otopis, nempel pada kompetisi-kompetisi pileg, pilkada dan pilpres”. Kelompok-kelompok intoleran etnosentris ini secara langsung ataupun tidak langsung telah membuat “branding visual, dan tradisi kostum baru, sebagai klain identitas fisik yang dipaksakan”. Seperti memakai sorban bergaya Timur Tengah dengan lautan warna putih serta bertaburan ayat-ayat suci dan dipolitisasi menjadi simbol-simbol gerakan, serta dibarengi dengan hujatan-hujatan yang rasis.
Kelompok ini jika diperhatikan juga membawa genetic etnosentris sebagai cermin keturunan RAS unggul. Dengan atas nama kebeneran agama dan membela Tuhan. Pada posisi yang lain juga kelompok intoleransi ini, telah melakukan peran keamanan yang sebetulnya menjadi domain negara. Hal-hal aktivitas masyarakat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan selera mereka dipastikan akan dihancurkan. Alasan utamanya adalah, bahwa negara dianggap tidak berdaya melawan kebatilan. Hingga dengan tega kelompok ini, juga merampas hak hidup masyarakat pedagang kaki lima, penjual makanan atas nama menghargai bulan puasa. Tindakannya adalah dengan jalan mengobrak-abrik dagangannya.
Weber: kekuasaan dan kekerasan adalah dua sisi dalam sekeping mata uang. Sebab kekuasaan diinterprestasikan kekerasan terselubung serta penampakan paling mencolok.
Jika dilihat kecenderungan dalam modernitas ini, selayaknya ada paradigma baru tentang pemahaman etnosentris. Sebab etbosentris didasarkan atas “kultutal dan tujuan gerakan permanen” maka hal ini bisa disebut memiliki etnosentris yang memadai indikatornya. Ada kontinyuitas, komitmen dan gaya hidup. Klop seperti etnosentris. Sehingga etnosentris juga disebut sebagai subkultur dan dihasilkan oleh suatu tindakan “berbentuk keyakinan”. Akumulasi berbentuk tindakan tersebut tidak saja berakar dan masif. Akan tetapi sudah “menjadi kebutuhan” bagi kaum toleran yang mengakar. Berbagai peristiwa pemberontakan apapun ideologi, kelompok, jenis isme-isme yang lain, seperti komunis, liberalism, kapitalisme dan seterusnya, termasuk demokrasi. Sudah menjadi tidak murni lagi. Dengan kata lain, terkoneksi, saling memasuki ideologi. Sehingga sulit sekali dikenali, bila dibandingkan dengan tumbuhnya isme-isme tersebut.
Hanah Arendt: kekuasaan bukan sebagai alat untuk memaksa orang lain. Melainkan pembentukan kehendak bersama dalam komunikasi saling memahami.
Kepentingan, keuntungan materi adalah akar terpenting berubahnya ideologi lokal etnosentris. Atau dengan kata lain etnosentris, menjadi baju yang harus diperbarui oleh “narasi-narasi pendukungnya”, siapa yang diuntungkan mendapatkan apa dan bagaimana. Jika hari ini isu-isu etnosentris masih laku keras digoreng, tentu kesakralannya sudah amat berbeda. Artinya ketika zaman kolonial, masih sangat strategis isu etnosentris, sebab lawannya adalah penjajah. Tapi sekarang lawan etnosentris adalah bangsa sendiri, yang sudah terkontaminasi mindsetnya dengan “produk-produk narasi penajajah”.
Sehingga semua penanganannya menjadi jauh lebih rumit. Karena semua itu terjadi politisasi akut dengan atas nama demokrasi. Substansi regulasi berbentuk undang-undang beberapa kali sudah mengalami perubahan-perubahan. Ujungnya masih berputar-putar tentang hal kekuasaan. Yang dibangun dengan aspirasi dari hasil reses DPR, berbentuk seremonial saja. Hanya supaya gugur kewajiban dan menjanjikan surga telinga. Sebab semua arah pertemuan tersebut difokuskan kepada kegiatan-kegiatan kecil. Bukan bertemunya arus pemikiran yang dapat memberikan kontribusi bagi strategi makro kepentingan negara bangsa. Disimpulkan disorientasi ini, secara sistemik akan menggugurkan marwah gerakan-gerakan etnosentris yang toleran maupun yang intoleran. Sebab kekaburan makna dalam gerakan ini sudah masuk “wilayah abu-abu”, karena ada hidden agenda. Intinya pengambilan peran ini telah merontokkan hal-hal ideal lokal.
Mungkinkah Kesadaran Kolektif Dibutuhkan?
Sisi lain yang diobok-obok adalah kehidupan beragama. Yang mayoritas menjadi penekan yang minoritas. Tapi hal ini pun perlu disanksikan, sebab tak sepenuhnya yang mayoritas memenangkan kompetisi kekuasaan. Jika yang minoritas punya uang dan kuasa, bisa saja dapat berbuat semaunya. Baik itu lewat kehidupan beragaman dengan berbagai tafsir untuk memojokkan lawan bicaranya atau dianggap musuhnya. Oleh karena itu muncul istilah “skripturalis”, bersifat difensif, berubah dan semakin memiliki keterbukaan.
Sedangkan “subtansialis”, mencoba terus semakin moderen untuk mendialogkan pesan moral dan ajarannya. Kedua kelompok ini terus berupaya mencari pola agar dapat bertahan dan hidup dalam perubahan. Dapat dipastikan kehendak tersebut, tentu akan membawa korban-korban baru yang tidak dapat dipastikan. Jika semua itu diatur oleh kelompok berpengaruh, dengan dasar terjadi politisasi dan kapitalisasi.
Foucoult: kekuasaan sebuah hubungan yang kompleks, melibatkan kekuatan-kekuatan dan menyebar ke seluruh bidang masyarakat.
Sekiranya sudah cukup, sedikit mewakili fenomena yang ada hari ini. Lalu apa yang dapat dipetik dari kekacauan tersebut? Sementara fakta kejadian intoleransi masih terjadi. Tarik menarik ajaran fundamental dengan bayang-bayang masa lalu diposisikan sebagai keluhuran dalam spiritualitas untuk memandang konsep negara bangsa. Pada posisi lain, ajaran-ajaran pendidikan, juga mengajarkan tentang konsep-konsep negara liberal yang memiliki makna “memuja kebebasan individu”. Bahkan sangat dicurigai sebagai ajaran-ajaran yang menjauhkan dari nilai-nilai humaniora. Intinya konsep ajaran liberal dianggap menghilangkan kesalehan sosial.
Salah satu pandangan terkemuka dari Muhammdiyah Safi’i Maarif, semakin meyakini bahwa negara agama di Indonesia tidak mungkin bisa diterapkan. Bukan saja Indonesia sebagai keberagaman (plural) RAS, akan tetapi kebutuhan perubahan pada pemikiran kontemporer (post strukturalis), telah meleburkan semua isme-isme yang satu dengan yang lain, saling toleransi, bukan lagi terkotak-kotak.
Machiavelli: kekuasaan dan moralitas adalah sesuatu yang berbeda tak dapat disatukan.
Gejala ini sebenarnya hampir terjadi disemua negara. Paham seperti komunisme, liberalism, demokrasi, kapitalisme telah mengalami degradasi atau penyesuaian-penyesuaian untuk mendekati “order perubahan”kaum konservatif dan kaum formalis, juga telah mengubah dirinya. Jika tak mau ketinggal kereta perubahan. Maka jalan satu-satunya adalah menyatukan pendapat bagi semua kepentingan-kepentingan terkait ideologi, sosial, politik dan ekonomi. Ada impian-impian tentang “good goverment” yang menjanjika kesejahteraan, keadilan, tertib hukum, tranparansi serta pendidikan gratis secara progersif.
Ini menarik sekali, walaupun perlu waktu dan energi besar untuk mewujudkannya. Yaitu capaiannya dengan mengembangkan konsep-konsep berbasis etika moral, kemanusiaan dan sufiktis. Hal ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi pada gaya hidup milenial. Yang sudah jenuh melihat perilaku rumit kaum elitis yang telah memiliki kecenderungan “neoliberalisme”. Walaupun perilaku elitis itu tidak ditampakkan secara terang-terangan. Akan tetapi gejala-gejala perebutan kekuasaan itu “sudah mencirikan intoleransi”. Utamanya pada basis-basis kekuaran mayoritas yang cenderung mengambil alih peran. Dan menentukan produk-produk regulasi “lewat voting”. Dan menisbikan konsep-konsep musyawarah mufakat. Tindakan ini tentunya membuat konsep kenegaraan berbasis Pancasila semakin kabur dan jauh dari arah ideologinya.
Suseno: kebebasan adalah mahkota dan martabat bagi manusia, yang terikat oleh moral dan etik bagi orang lain.
Pluralisme, kebhinekaan, kemanusiaan, teologi, kesejahteraan, adalah konsep sangat hebat, mungkin taka da duanya di dunia. Pancasila, sekali Pancasila yang mampu mempersatukan kepentingan di dunia maya pada ini. Pancasila adalah konsep “koneksitas Timur”, yang menghubungkan antara manusia dengan manusia (kesalehan sosial kemanusiaan), manusia dengan semesta alam (adalah sistem) keteraturan/bertemunya makro kosmos dan mikro kosmos. Termasuk pemerintahan. Menyatukan manusia dengan Tuhannya.
Trilogi ini sangat ampuh untuk mewadahi untuk keberagaman kepentingan. Musuh utama Pancasila adalah oligarki, monopoli, fermentasi kuasa politik, intoleransi, kapitalis anarkis. Pancasila sebagai tuntunan negara bangsa sulit dijalankan ketika sekolompok elit selalu dan selalu mempolitisasi nilai-nilai luhur demi kepentingan kelompknya. Semoga kesadaran bersama utamanya kaum milenial, tidak terpengaruh oleh sengketa kepnetingan masa lalu, diharapkan dapat mewujudkan negara bangsa yang bermartabat. Serta mampu bersaing tanpa meninggalkan identitas bangsa, baik secara formal maupun substansial. (Tancep Kayon, Bumiaji 8 Desember 2022)


