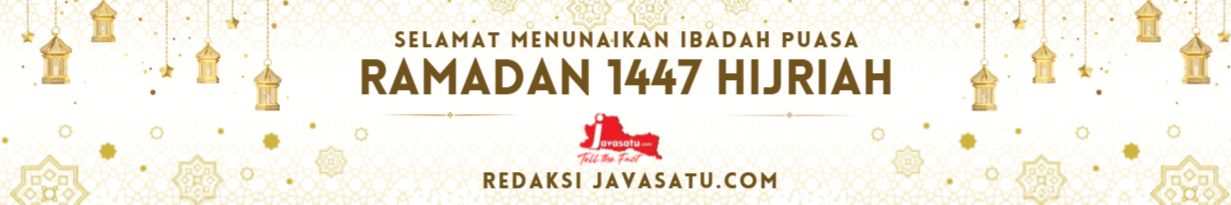Jalan Sepi Simbol Relasi Sosial
Oleh: Slamet Hendro Kusumo
Masyarakat tradisional, hampir di seluruh nusantara memiliki rumpun kebudayaan dengan nilai-nilai hidup hampir berhimpitan. Hidupnya selalu menekankan relasi kekerabatan yang sangat kental. Termasuk dalam masyarakat Jawa, satu dengan lainnya saling berempati. Artinya saling memberikan empati, yaitu bentuk perhatian konkrit antar individu dalam masyarakat pedesaan. Masih sangat memegang nilai-nilai luhur, warisan leluhurnya. Tanah pekarangan masih sangatlah luas, sehingga halaman untuk bermain anak-anak ketika pulang sekolah juga sangat luas. Sehingga halaman itu menjadi bagian penting yang menghubungkan antara anak-anak dan keluarga.
Sudah menjadi kebiasaan/tradisi, setelah anak-anak selesai bermain atau sedang istirahat. Empunya yang punya rumah “cemilan polo pendem”. Maka dengan riang gembira anak-anak tersebut menyantapnya dengan lahap. Tidak lupa “matur nuwun” kepada yang memberinya. Kebahagiaan anak-anak juga kebahagiaan masyarakat desa. Di kanan kiri halaman rumah tertanam sejumlah jenis buah-buahan lokal. Siapapun diizinkan, boleh mengambil secukupnya untuk di makan. Asal bukan diambil untuk dijual ke pasar. Ketika musim panen, dengan ranumnya buah-buahan tersebut, menjadi daya tarik siapapun yang melihat surga dunia itu. Tak terkecuali orang kota. Bahkan orang kota banyak membeli suasana desa itu, hanya untuk mengenang nenek moyang dan menikmati suasana baru, agar lepas dari rutinitas.
Bakker (2019): kebudayaan meliputi penciptaan, perkembangan, nilai yang ada dalam fisik, personal serta sosial, dan disempurnakan sebagai realisasi tenaga manusia dan masyarakat.
Kearifan masyarakat desa hampir rata-rata tidak menggunakan pagar pembatas. Jika ada pagar pembatas bisa berbentuk, terasiring atau tanaman keras buah-buahan. Sehingga anak-anak kecil dapat bermain sesukanya, tanpa ada halangan pembatas. Jika ada pagar, rata-rata tanaman perdu seperti daun luntas, dapat dibuat sayuran untuk dibuat botok dan sayur lodeh. Ada juga tanaman rambat seperti simbukan, perdu katu, perdu kelor, juga materi bahan pangan organik. Ditambah sayuran liar yang tumbuh di mana-mana, seperti menyeng, tumbaran, katul dan banyak lagi. Semua tanaman itu sehat dan jauh dari pengaruh residu.
Bentuk-bentuk nilai kekerabatan ini sudah berlangsung ratusan abad. Melahirkan ribuan generasi. Pranata budaya ini, konsep utamanya adalah relasi sosial, yaitu sikap memberi, saling melindungi. Dicontohkan ketika ada tetangga membangun rumah. Kebetulan tanahnya ada dibelakang rumah tetangga dan ingin meminta jalan masuk, tanpa syarat jual beli, pasti diberikan secara cuma-Cuma. Bahkan luasan jalan rata-rata diberi jauh lebih lebar daripada permintaan awal. Sebab diyakini dalam ajaran falsafah leluhurnya khususnya dalam budaya Jawa orang yang mau memberikan jalan bagi sesama dimitoskan masuk surga. Setidaknya surga dunia. Di situ ada hormat bagi yang diberi. Kekuatan hubungan sosial akan lebih dekat, salah satunya adalah saling memberikan masakkan antar tentangga. Hal ini sudah menjadi kelaziman masyarakat desa. Sebab makna dan filosifi jalan, telah menjadi lalu lintas kepentingan manusia siapapun mereka. Apa terkait dengan kendaraan lokal seperti gerobak dorong, cikar, dan sejenis kendaraan lain.
Bekker: kebudayaan subjektif adalah aspirasi fundamental dan berkembangnya kebenaran, kebajikan dan keindahan.
Jika jalan itu sudah dimanfaatkan dengan baik, serta bermanfaat. Disitulah letak kebahagiaan yang menetramkan pribadi sang pemberi jalan. Sebab jalan yang baik akan memberikan berkah bagi kehidupan manusia. Di jalan itulah, akar peradaban di mulai dengan optimis sangat tinggi. Karena semua atensi lingkungan memberikan dukungan bukan saja jalan sebagai unsur materialistik. Namun jalan juga sebagai strategi kebudayaan, cara berpikir manusia untuk mendukung populasi dan berkembanganya sirkulasi ekonomi. Maka fungsi jalan akan berdampak kepada murahnya ongkos angkut, mempercepat pasca panen, untuk diangkut ke pasar tradisional.
Potret Sosial Masyarakat Desa
Mengamati secara cermat tentang kearifan lokal akan tergambarkan suatu panorama, kecerdasan, cara berpikir, pranata kebudayaan, adat istiadat serta tata cara hidup masyarakat setempat. Khususnya pada nilai-nilai luhur sebagai konvensi kebudayaan. Tentunya akan didapatkan bagaimana masyarakat tersebut memproteksi dirinya, hubungannya dengan alam, hubungan dengan Tuhan. Perkembangan atau konsep tumbuhnya individu, kepada lingkup kecil, yakni keluarga tersebut. bahwa seorang anak, sedikit atau banyak pasti akan dipengaruhi oleh gaya hidup orang tuanya. Paling sederhana adalah perilaku dan tindakan agar dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Antara lain, dapat membedakan baik buruk. Ini milik sendiri boleh diambil, yang itu milik orang lain boleh diambil jika ada izin dari yang punya. Ajaran perilaku dan tindakan memiliki sebab akibat. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka akan mendapatkan konsekuensi dari sebab atau perbuatan. Salah satu hak dan kewajiban pribadi, keluarga menjadi akar tumbuhnya kebaikan-kebaikkan, kebajikan untuk menghadapi lingkungan di luar teritorial keluarga. Oleh karenanya, jika pendidikan moral dari keluarga tersebut dilanggar, hukuman keluarga akan diberlakukan. Walau setiap keluarga memiliki cara berbeda akan sanksi-sanksi sebuah pelanggaran. Namun jika perbuatan ini, juga merugikan orang lain di luar keluarganya maka sanksi sosial dan hukum baik adat maupun formal, juga akan diberlakukan.
Kluckhohn: kebudayaan adalah kecakapan adat, akhlaq, kesenian, ilmu dan lain-lain. Dimiliki oleh manusia sebagai subjek masyarakat.
Bagian kedua ini bahwa kunci kearifan keluarga basis utamanya adalah tentang hubungan individu dengan lingkungan sekitar. Dapat dibagi menjadi dua hal yaitu wilayah sosial terkait dengan alam dan masyarakat. Tentang alam sebenarnya manusia desa atau Jawa, kesadaran hidup sangatlah bergantung pada kehadiran alam. Utamanya masyarakat petani. Jika ditarik benang merah, uraian tersebut akan terlihat sejauh mana sikap dan empati masyarakat desa agar dapat bertahan hidup. Yaitu membudidayakan segala jenis tanaman sebagai bahan pangan keseharian. Tindakan ini sudah dilakukan secara turun-temurun, ada konvensi keluarga dan konvensi lingkungan. Gerakan masal ini, menciptakan perilaku secara kontinyu, konvensi dan gaya hidup. Dengan demikian gerakan masal ini, karena dilakukan secara serentak, maka bahan pangan menjadi sangat berlimpah. Bahkan posisi uang sebagai alat tukar, tidak terlalu dominan seperti masyarakat perkotaan. Semua kegiatan terukur lewat hal-hal bersifat materi. Sebab masyarakat sudah kesulitan menanam sesuatu, terkait dengan bahan pangan. Istilah lain, masyarakat kota buka masyarakat agraris melainkan masyarakat jasa. Hidupnya tergantung kepada jasa untuk mendapatkan materi.
Serat Jayabaya: ukum agama dilanggar (hukum agama dilanggar), artinya kemuliaan agama dijadikan bahan lelucon serta dilanggar. Atas nama demokrasi menjadi hambatan, perlawanan, karena tekanan kuasa politik. Sedangkan hukum yang berasal dari Tuhan terabaikan. Yang muncul adalah sarang kejahatan, tidak manusiawi.
Pada bagian ketiga, manusia dengan Tuhan. Dalam masyarakat Jawa disebut manunggale kawulo Gusti. Yaitu perjalanan spiritual tentang kedekatan dan penyatuannya manusia dengan Tuhannya. Seperti diketahui bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat yang memiliki hubungan holistik. Ada keterikatan dan keterkaitan antara manusia dengan manusia, manusia dengan semesta alam, manusia dan Tuhan. Khususnya pengertian Tuhan ada dua jenis yaitu, pertama Tuhan, atau dengan kata lain “ana ning ora ana”. Kedua sedangkan Tuhan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah perwujudan Bapa Biung, yaitu Gusti ingkang katon. Artinya wakil Tuhan yang ada di bumi. Bapa Biung tersebut diberi tempat amat tinggi serta derajat dimuliakan, oleh keturunannya.
Gusti ingkang katon yaitu Bapa Biung sebagai wakil ana ning ora ana oleh karena itu tidak ada seorang anak tidak akan menelantarkan atau menitipkan orang tuanya ke yayasan panti asuhan. Setidaknya jika kedua orang tuanya itu tidak memiliki keturuan langsung, maka sanak kadangnya baik yang lebih muda atau punya hubungan sedarah akan merawat serta melindungi hingga purna tugas. Pada situasi yang lain, jika usia orang usia lanjut tersebut tidak punya saudara dan anak maka lingkungan akan memelihara. Intinya posisi orang tua dari tradisi orang Jawa menjadi perhatian dan utama dalam konsep humaniora. Yaitu bahwa orang tua adalah pusaka buat anak-anaknya. Jika anak anaknya mengabaikan orang tua mereka akan dapat sanksi sosial atau murtad.
Serat Jayabaya: akeh wong mendem dunga, banyak orang berdoa tapi tidak terkabul, sebab tidak pasrah, nabi dan Tuhan dilalaikan. Dan lebih suka berkawan dengan nafsu, serupa setan.
Tingkat spiritualitas tertinggi adalah Tuhan/Gusti ana ning ora ana. Oleh sebab itu masyarakat Jawa meyakini Gusti sebagai “pemberi segalanya”. Menjadi tujuan dalam puncak kehidupan yang abadi. Hal tersebut dapat terwujud jika dapat mengendalikan diri dengan baik dan benar. Sebab rasa jati adalah pusat dari segala gerak hidup, yaitu obah. Obah adalah kuasa hidup, dinamis, ada keselarasan, tidak dibebani oleh pemikiranm panca indera, akal budi, karena itu dapat menjebak, menipu. Dengan demikian paradigma orang Jawa untuk menempuh kedekatan dengan Gustinya ialah mewujudkan spirit suwung. Tidak butuh apa-apa, tidak perlu apa-apa, tidak ada keinginan apa-apa, kecuali menyerahkan seluruh hidup kepada Gusti. Dengan gelundung, mengalir dan meningkatkan kesadaran, untuk menerima konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan Gusti.
Perubahan dan Kepentingan Hidup
Dalam kehidupan manusia, tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Perubahan itu di mulai dari manusia itu sendiri (individu), lingkungan, dan regulasi. Ketika manusia mulai dilahirkan, sudah diajari paling awal untuk mengenali dan dikenalkan oleh kedua orang tuanya, apa dan siapa dunia ini, serta bagaimana cara mengenali juga menghadapinya. Pemahaman mengenali dan memahami ini adalah inti dasar atau konsep dalam tindakan yang menggiring manusia cilik itu untuk diberi kesempatan berinisiatif, mengubah. Pada praktiknya adalah memindahkan atau merusak mainan anak-anak yang diberikan, walau itu masih dilakukan secara instingtif.
Deleuze (2011), kebijakan-kebijakan asketik, bukan tujuan akhir dari kebajikan moral, atau saran religius, untuk mencapai kehidupan lain. Namun lebih sebagai akibat pemikiran filosofisnya sendiri.
Berikutnya adalah pendidikan, diajarkan bagaimana menguasai ilmu pengetahuan dengan membaca berbagai ilmu, bagaimana manusia dapat bertahan hidup. Diberikan ujian-ujian sekolah bagaimana cara menggunakan otak, berpkir dan melakukan tindakan. Muatan-muatan untuk mengubah sesuatu secara sistemik dan masif menjadi inti radikal yang akan mengubah secara permanen. Dapat disimpulkan, secara sengaja bibit perubahan itu sudah ditanamkan secara terus menerus. Jika dicermati secara lebih jauh, sebenarnya iklim kompetisi tersebut by design, direncanakan dengan “hasrat kuasa” hal inilah yang menciptakan arus besar tak terhindarkan. Disebut “peran kepentingan” ujungnya akan membawa dampak perubahan pada hidup manusia serta lingkungannya. Bisa menjadi lebih baik, atau justru menghancurkan. Heritage masa lalu yang luhur.
Spinosa (2018): kehidupan tidak lagi dijalani atas dasar kebutuhan, sarana, dan tujuan akhir. Namun memiliki keterkaitan produksi, produktifitas. Potensi sebab-akibat.
Selanjutnya hadirnya regulasi, kapitalisasi yang tidak membuat manusia lebih manusiawi. Memang semua tindakan dan akibat tergantung pada manusia itu sendiri. konvensi-konvensi kuasa, keputusan dipercayakan kepada mayoritas suara (demokrasi). Namun bagaiman jika yang mayoritas memiliki kuasa hak prerogatif dan mampu menggerakkan regulasinya. Sehingga kuasa mayoritas dan minoritas, sebenarnya bukan lagi menjadi acuan dalam menentukan kebijakan.
Akan tetapi pengaruh kuasalah yang menentukan. Dicontohkan, lahirnya undang-undang agrarian tentang hak kepemilikan tanah (sertifikat), menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam kenyataannya menjadikan manusia lebih mendahulukan haknya daripada kewajiban. Seperti kasus-kasus sejengkal tanah pada kepemilikkan yang ada di kota padat penduduk, rela urusan hukum bahkan kehilangan nyawa demi mempertahankan haknya, walaupun sejengkal tanah. Regulasi tentu bertujuan baik akan tetapi tanggapan, kepentingan untuk bertahan hidup tanpa dilandasi akal sehat, keteladanan akan membentuk manusia bengis, jahat dan ngawur. (Slamet Henkus – Tancep kayon, 10 Oktober 2022)
Biodata Penulis
Penulis, Slamet Hendro Kusumo (Henkus) lahir di Batu, 5 Mei 1959 adalah seorang pekerja seni lukis/rupa di Batu.
Menyelesaikan pendidikan program doktor (S3) Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang tahun (2021). Aktif mengadakan pameran seni rupa diberbagai kota di Indonesia dan dibeberapa Negara. Sejak 1979 hingga 2022.
Slamet Henkus kini mengelola Omah Budaya Slamet (OBS), yang didirikan tahun 2002.
Bergerak dalam kegiatan dan pemikiran kebudayaan, dan lain-lain. Slamet Henkus aktif sebagai narasumber di bidang filsafat, sosiologi, politik dan kebudayaan antara lain di Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri, Universitas Kanjuruhan, Pamong Kebudayaan Jawa Timur, sejumlah UKM diberbagai perguruan tinggi, komunitas-komunitas independen di berbagai wilayah Indonesia, sejumlah perguruan tinggi Amerika saat berkunjung di OBS, sejumlah partai politik dan beberapa Dinas Pemkot Batu.
Slamet Henkus juga sebagai Penulis Esai di media online seperti KlikTime, BeritaRayaOnlineMalasya, Javasatu.
Segudang penghargaan diterima Slamet Henkus antara lain, pembuatan Buku Pesona Kota Batu tahun 1988 oleh Bupati Abdul Hamid, sebagai Panwascam Batu 1999 oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, terpilih 5 Besar Pra biennale Bali Jawa Timur 2004, Penghargaan DPRD Kota Batu sebagai penggagas, pemikir dan penggerak dalam peningkatan status Kotatif Batu tahun 2009 dan 2014, salah satu (milestone artist) Biennale Jatim 6 tahun 2015, Encompass Awards tahun 2016 (dari Encompass Indonesia), penghargaan “Kreator Bidang Seni Rupa” tingkat Jawa Timur tahun 2016 oleh Gubernur Jawa Timur, Tourism Awards dari Walikota Batu sebagai Budayawan tahun 2021.
Kini Slamet Henkus diberikan amanah menjadi Dewan Penasehat Forum Pamong (FPK) Kebudayaan Jawa Timur (2022). Selain itu, mengemban tugas menjadi Ketua Dewan Penasehat Persatuan Penulis Indonesia Satupena Jawa Timur.